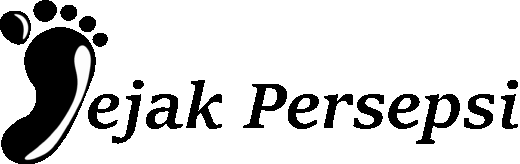Purwokerto – Ahmad Tohari tersenyum tipis ketika mengenang awal perjalanannya di dunia jurnalistik. Bukan berawal dari ruang redaksi, melainkan dari kegemarannya membaca koran sejak remaja. “Sejak umur 15 tahun saya sudah suka membaca koran. Tahun 80-an ada lowongan redaktur di Jakarta, saya iseng melamar, ikut tes, dan ternyata diterima,” kisahnya.
Sejak saat itu, Tohari menekuni profesi wartawan sekaligus redaktur di sebuah harian nasional. Dari masa mesin tik hingga era digital, ia merasakan langsung perubahan dalam dunia pers. “Dulu, menulis berita repot sekali. Semua pakai mesin tik, tidak ada internet, tidak ada HP. Sekarang berita bisa langsung sampai ke layar redaktur dalam hitungan menit,” ungkapnya. Namun, ia menegaskan, kecepatan bukan berarti kebenaran. “Risikonya, berita sekarang bisa saja hoaks. Kalau dulu, orang tidak akan repot membuat berita palsu dengan mesin tik,” tambahnya.
Sebagai jurnalis senior, Tohari percaya bahwa wartawan sejati lahir dari hobi membaca. Baginya, membaca melatih jiwa literasi dan membuka cakrawala. “Kalau orang tidak suka membaca, sulit jadi wartawan. Karena wartawan punya tugas membela masyarakat, dan itu berarti objektivitas harus dijunjung tinggi,” tegasnya.
Meski begitu, ia tak menutup mata pada tantangan integritas. Fenomena “wartawan bodrek”—istilah untuk wartawan yang datang sekadar untuk menerima amplop pejabat—masih segar dalam ingatannya. “Prinsip dasar seorang jurnalis ya kejujuran. Kalau wartawan sudah geser dari integritasnya, menurut saya itu wartawan palsu,” ucapnya lugas.
Bagi Tohari, jurnalisme bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah moral. Ia menutup pesannya untuk mahasiswa dengan penuh penekanan: “Memberikan kabar dan keterangan kepada masyarakat itu jasa yang mulia. Tapi kalau hanya menulis ulang tahun artis lalu diberi amplop, nah itu bukan wartawan.”
Dan dari tuturannya, jelas bahwa bagi Ahmad Tohari, jurnalisme sejati bukanlah tentang cepat menulis atau mengejar sensasi, melainkan tentang keberanian menjaga kebenaran.
Editor: Wanda Apriliani