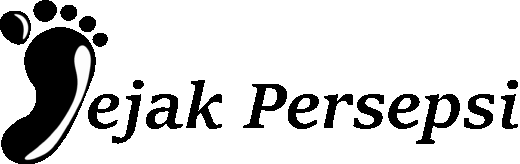Purwokerto — Malam 11 Desember 2025 menjadi ruang waktu bagi pementasan drama Orang-Orang di Tikungan Jalan karya W. S. Rendra. Sejak lampu panggung diredupkan pada pukul 19.45 hingga pertunjukan berakhir sekitar pukul 20.20, suasana tenang menyelimuti tikungan jalan yang sederhana, tetapi sarat makna. Tidak ada pembukaan yang gegap gempita. Kesunyian justru menjadi pintu masuk, seolah penonton diajak berhenti sejenak dari dunia luar dan berdiri bersama tokoh-tokohnya di sudut jalan yang dingin dan penuh pertanyaan.
Pertemuan Djoko dan Sri menjadi pintu masuk kisah. Percakapan mereka mengalir ringan, bahkan cenderung menggoda. Pujian tentang paras, tubuh, dan malam yang panjang terucap tanpa beban. Namun, di balik dialog yang tampak santai itu, tersimpan kegelisahan yang perlahan terkuak. Sri bukan sekadar perempuan yang menemani malam. Ia adalah manusia dengan sejarah panjang yang tidak pernah benar-benar selesai.
Ketika Sri bertanya tentang pernikahan dan Djoko menolak melangkah sejauh itu, penonton disuguhi ironi relasi manusia. Ada keintiman tanpa tanggung jawab. Ada kebersamaan tanpa kepastian. Malam terasa panjang, tetapi arah hidup tetap kabur. Adegan ini berjalan tenang, nyaris tanpa tekanan, tetapi justru di situlah letak kekuatannya.
Suasana berubah ketika penjual wedang kacang masuk ke panggung. Kehadirannya menghadirkan denyut kehidupan kelas bawah yang akrab dengan jalanan. Wedang kacang bukan hanya minuman penghangat, melainkan simbol singgah sementara bagi orang-orang yang lelah. Di sela-sela itu, terdengar suara harmonika La Paloma yang dimainkan seorang pemuda gila, anak dari Surya, yang sepanjang malam berteriak mencari bapaknya. Teriakan itu menembus sunyi dan menghadirkan kegelisahan yang tak terucap oleh tokoh lain.
Tokoh Botak muncul sebagai sosok asing yang ringan langkahnya, ramah, dan tampak ceria. Namun, di balik kelucuannya, Botak menyimpan kepekaan sosial. Ia menjadi saksi berbagai tragedi kecil di tikungan jalan itu. Ketika seorang perempuan bernama Iyeng ditipu dan dipukul pelanggannya, Botak berdiri paling depan. Adegan ini menjadi salah satu momen paling getir dalam pementasan. Tangisan Iyeng yang meraung tentang usia dan kehancuran martabatnya menggema lama di telinga penonton.
Sri kemudian membuka kisah hidupnya. Dengan suara datar, ia menceritakan kehilangan orang tua akibat perang, pengalaman pengungsian, kelaparan, hingga keterjerumusannya ke lapisan hidup paling bawah. Tidak ada isak tangis berlebihan. Justru ketenangan dalam bercerita itulah yang membuat kisahnya terasa kejam. Penonton disadarkan bahwa kemiskinan, stigma, dan kekerasan sosial tidak selalu lahir dari pilihan, melainkan dari keadaan yang memaksa.
Pementasan semakin pekat ketika Surya masuk ke panggung. Ia adalah pemabuk, lelaki yang terhuyung dengan botol minuman keras di tangan, melantunkan sajak dengan suara serak. Puisinya tentang mabuk, duka, dan pelarian hidup terdengar getir sekaligus putus asa. Surya bukan sekadar tokoh pemabuk. Ia adalah simbol kegagalan manusia menghadapi luka batin yang terlalu berat.
Kehadiran Surya memunculkan ironi yang menyayat. Pemuda gila yang sejak awal berteriak mencari ayahnya ternyata adalah anak Surya sendiri. Seorang anak yang tidak mengenali bapaknya, dan seorang bapak yang tenggelam dalam mabuk untuk melupakan kenyataan. Hubungan ayah dan anak itu terputus bukan oleh jarak, melainkan oleh luka dan keputusasaan.
Di tengah suasana yang muram dan reflektif, ketegangan sempat pecah oleh adegan tak terduga ketika Surya tiba-tiba memukul tempat jualan pedagang wedang kacang. Tindakan spontan itu mengundang tawa penonton. Gelak tawa terdengar lepas, sejenak memecah beban emosi yang mengendap sejak awal pertunjukan. Namun, tawa itu segera terasa pahit, karena penonton sadar bahwa kekerasan tersebut lahir dari mabuk dan frustasi, bukan dari kelucuan semata.
Pementasan ini bergerak perlahan, tetapi tidak pernah kosong. Setiap tokoh membawa cerita, setiap diam menyimpan makna. Orang-orang di tikungan jalan itu tidak sedang mencari kebahagiaan besar. Mereka hanya ingin bertahan satu malam lagi, dengan cara masing-masing.
Ketika suara harmonika kembali terdengar dan cahaya panggung meredup, penonton tidak sekadar menyaksikan akhir pertunjukan. Mereka diajak merenung tentang manusia-manusia yang kerap terabaikan. Tentang perempuan yang ingin keluar dari stigma, tentang pemabuk yang kalah oleh luka, tentang anak yang berteriak memanggil ayahnya, dan tentang tikungan jalan yang menjadi saksi bisu semuanya.
Drama Orang-Orang di Tikungan Jalan berhasil menghadirkan realitas sosial dengan cara yang tenang, pahit, dan jujur. Tanpa menggurui, pementasan ini memperlihatkan bahwa di sudut-sudut kota, selalu ada manusia yang hidupnya berbelok tanpa pernah benar-benar sampai ke tujuan.
Editor: Alifia Rizqi Ramadhan