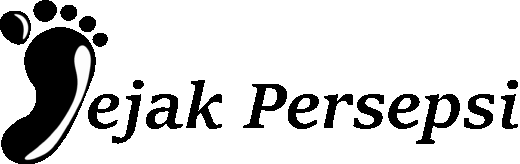Purwokerto – Lampu aula perlahan meredup, meninggalkan bisik penonton yang saling berbaur dalam rasa penasaran. Malam itu, Aula Bambang Lelono, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, tidak sekadar menjadi ruang pertunjukan biasa. Kamis, 11 Desember 2025, pagelaran teater Jagat Rasa menghadirkan salah satu pementasan Orang-Orang di Tikungan Jalan, karya W.S. Rendra, yang membawa realita kehidupan jalanan ke atas panggung dan mengajak penonton menyelami kisah orang-orang yang hidup di sudut realita.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Panggung Jagat Rasa malam itu menampilkan kesederhaan yang terasa dekat dengan kehidupan. Ruang pertunjukan dihadirkan menyerupai sudut jalanan tempat cerita bermula. Sebuah gerobak wedang kacang menepi sejenak, menunggu mangkuk yang masih berpindah tangan sebelum kembali berputar melayani, lampu jalan menggantung dengan cahaya yang nyaris redup, sementara dindingnya dipenuhi tempelan poster dan selebaran usang. Detail-detail tersebut perlahan menghidupkan suasana, menghadirkan potret kehidupan masyarakat kecil yang akrab dengan keterbatasan, tetapi sarat akan cerita.

Di tengah tata panggung yang sederhana, kisah bergerak pelan. Djoko, seorang pemuda yang datang dengan langkah berat, memilih singgah di Jalan Puspa, tempat orang-orang terluka mencari pelarian. Wajahnya menyimpan rasa kecewa yang tak terucap. Cinta yang ia yakini ternyata berujung pengkhianatan, dan jalanan menjadi satu-satunya tempat yang memberinya rasa diterima. Duduk di antara hiruk-pikuk yang sunyi, Djoko tampak terjebak antara keinginan untuk melupakan dan ketidakmampuan untuk benar-benar pergi.
Di dekatnya, Sri hadir sebagai sosok perempuan jalang yang menjalani hidup dengan caranya sendiri. Gesturnya tenang, tutur katanya lugas, seolah telah berdamai dengan stigma yang melekat pada dirinya. Sri bukan sekadar simbol perempuan jalanan, tetapi potret manusia yang bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Interaksinya dengan Djoko memperlihatkan dua luka yang berbeda, namun bertemu di ruang yang sama dan menampilkan persinggungan emosi, kekecewaan, serta pilihan hidup yang lahir dari luka personal masing-masing.
Tak jauh dari mereka, tokoh Botak dengan topi yang selalu bertengger di kepala duduk mengamati. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya memberi warna tersendiri dalam dinamika panggung. Botak menjadi saksi bisu percakapan, pertengkaran, dan keheningan yang terjadi di tikungan jalan itu. Sosoknya seolah mewakili orang-orang yang hidup di pinggir cerita, tetapi tetap menjadi bagian dari denyut kehidupan jalanan.
Melalui pertemuan Djoko, Sri, dan Botak, Jagat Rasa menghadirkan realita sosial yang tidak hitam putih. Jalanan bukan sekadar tempat singgah, melainkan ruang pertemuan bagi manusia dengan luka masing-masing. Di sanalah cerita mengalir, tentang cinta yang patah, hidup yang terpaksa dijalani, dan harapan kecil yang tetap bertahan meski sering diabaikan.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Di sudut lain panggung, perhatian penonton tertuju pada sosok Surya. Dengan tubuh sedikit condong ke depan, satu tangannya terangkat menunjuk ke arah yang tak pasti, sementara tangan lainnya menggenggam botol minuman keras. Gerak tubuh dan ekspresi wajahnya meluapkan kegelisahan hidup yang seolah tak pernah menemukan ujung.
Dalam adegan itu, Surya berdiri di antara tokoh-tokoh lain yang duduk terdiam, menegaskan posisinya sebagai figur yang paling gelisah sekaligus paling terluka. Wajahnya memancarkan ketegasan yang rapuh, sebuah potret ayah yang tenggelam dalam kebiasaan mabuk, yang kelak menyisakan luka batin dan jarak dengan anaknya sendiri. Surya tidak sekadar hadir sebagai pelengkap cerita, melainkan menjadi suara paling lantang yang menyuarakan kegelisahan kehidupan di tikungan jalan.
Kostum yang dikenakannya, dipadu dengan gestur tubuh yang lepas dan nyaris tanpa kendali, memperkuat karakter Surya sebagai manusia yang tersisih namun penuh kesadaran sosial. Dialog-dialog yang ia lontarkan terdengar kasar, tetapi justru jujur, mewakili keresahan masyarakat kecil yang hidup di persimpangan nasib. Di sekelilingnya, tokoh-tokoh lain menyimak dalam diam, membiarkan Surya menjadi pusat konflik sekaligus cermin realita sosial yang diangkat dalam pementasan ini.
Tak jauh dari Surya, Narco hadir sebagai bayang-bayang masa lalu yang tak ingin diakui. Pemuda yang dicap gila itu memilih jarak, baik secara fisik maupun batin. Dalam lakon ini, Narco menolak menyebut Surya sebagai ayahnya, menjadikan hubungan keduanya sebagai konflik batin yang sunyi namun tajam. Penolakan itu bukan sekadar sikap, melainkan bentuk perlawanan atas luka dan kehidupan yang tak pernah ia pilih serta jarak emosional inilah yang terus membayangi langkah Surya di panggung.
Ketika lampu panggung kembali menyala dan para pemeran menundukkan kepala, kisah di tikungan jalan itu tidak serta-merta berakhir. Di tikungan jalan yang dihadirkan Jagat Rasa malam itu, panggung menjadi ruang pengakuan bagi luka-luka yang selama ini dipendam. Kisah tentang cinta yang dikhianati, hidup yang dijalani dengan terpaksa, hubungan darah yang retak, hingga kegelisahan yang diluapkan dalam diam, bertemu dalam satu ruang yang sama. Cerita ini tinggal di benak penonton sebagai potongan-potongan realita yang dekat, pahit, dan nyata.
Melalui Orang-Orang di Tikungan Jalan, pagelaran teater Jagat Rasa tidak sekadar menghadirkan pertunjukan, tetapi membuka ruang perenungan tentang manusia-manusia yang hidup di persimpangan nasib, tentang luka yang diwariskan, pilihan yang terpaksa diambil, dan harapan kecil yang tetap bertahan di tengah kerasnya hidup. Di panggung sederhana itu, suara-suara yang sering luput dari perhatian akhirnya menemukan tempat untuk didengar. Melalui Orang-Orang di Tikungan Jalan, pagelaran teater Jagat Rasa mengingatkan bahwa realita sosial bukan sekadar cerita orang lain, melainkan cermin kehidupan yang kerap kita hindari, namun terus berdiri di hadapan kita.
Editor: Rizqi Khoirunnisaa Afriana