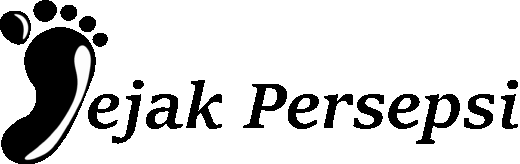Purwokerto—Sebuah pameran foto tengah dipajang. Sebuah adegan teater membeku dalam gambar yang dramatis. Di balik setiap hasil jepretan yang memikat dalam acara “Jagat Rasa” yang diselenggarakan pada10—12 Desember 2025 itu, tersimpan pelajaran yang lebih dalam daripada sekadar teknik kamera. Bagi para panitia dokumentasi, proyek kolosal mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 ini ternyata adalah sekolah kehidupan yang intens. Di sana, mereka tidak hanya belajar menata ISO dan shutter speed, tetapi lebih tentang kepekaan menangkap momen, ketangguhan fisik, dan arti kesiapan yang sering terabaikan.
Jagat Rasa, yang memadukan pementasan tiga teater dan pameran fotografi di Aula Bambang Lelono, Fakultas Ilmu Budaya, memang dirancang sebagai puncak ekspresi kreatif. Namun, bagi divisi dokumentasi, acara ini adalah sebuah simulasi lapangan yang menuntut lebih dari sekadar hobi. Mereka harus menjadi pencerita visual yang sigap, mengantisipasi plot, dan memahami emosi karakter untuk mengabadikannya menjadi sebuah narasi diam. Inilah medan tempat teori fotografi bertabrakan dengan realitas panggung yang dinamis dan tak terulang.
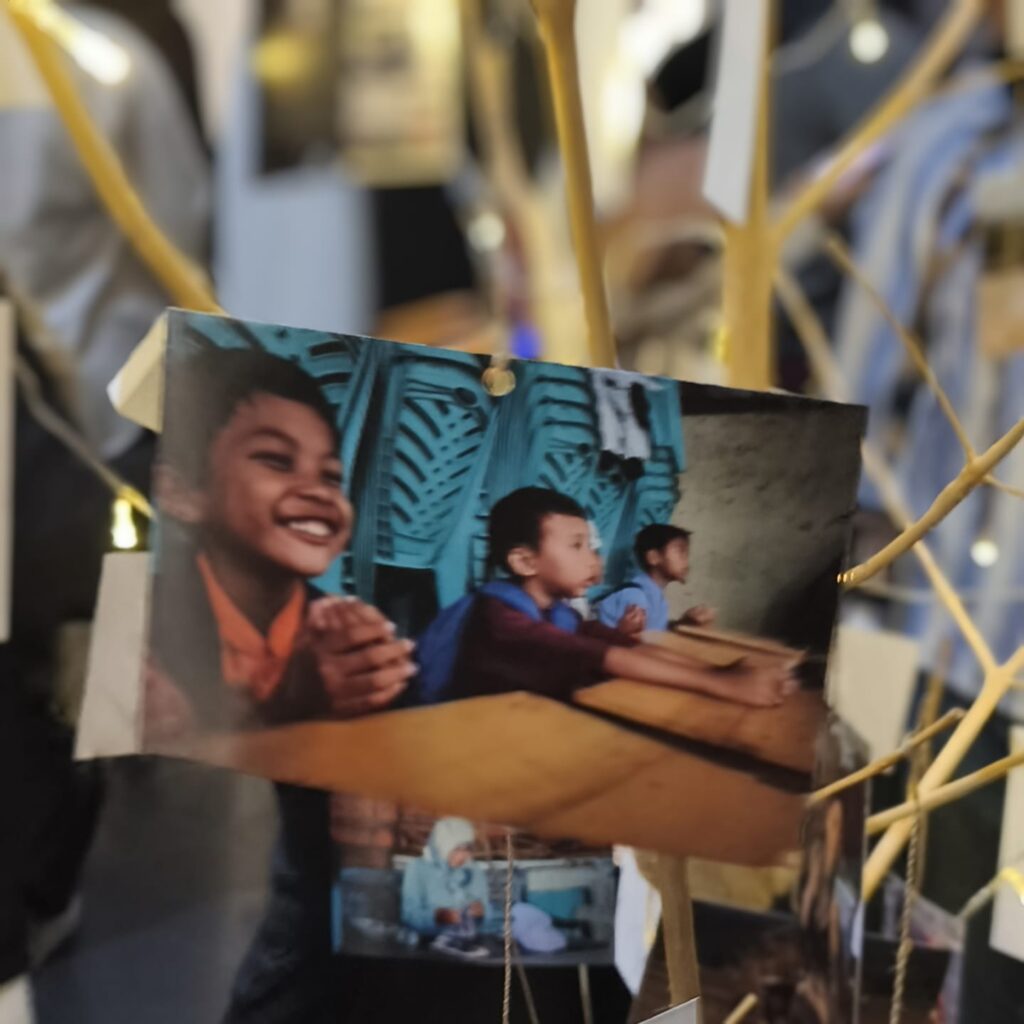
Syifa, salah satu panitia dokumentasi yang menekuni fotografi, mengakui bahwa proyek ini adalah pengasah skill yang nyata. “Kamera yang bagus tapi lensanya jelek, gak bakalan jadi bagus,” ujarnya, menyentuh dasar fotografi yang paling praktis. Kemampuan mengatur setting teknis seperti ISO dan shutter speed menjadi latihan wajib. “Itu berguna banget… ‘Aku harus begini, aku harus begini,'” katanya, menggambarkan keputusan cepat yang harus diambil di tengah tekanan acara.
Namun, pelajaran terbesar justru melampaui hal teknis. “Lebih ke peka aja sih terhadap sekitar,” tutur Syifa. Ia menjelaskan, memiliki kamera canggih pun tak berarti apa-apa jika kehilangan momen. Ia mencontohkan mimik wajah aktor yang sempurna untuk sebuah adegan. “Terus kita nggak jepret, tuh kayak, ‘Loh!’ ceritanya gak ada… yang paling penting adalah momen,” tegasnya. Di sinilah fotografi bertransformasi dari aktivitas menjepret menjadi seni berempati dan hadir sepenuhnya.
Selain kepekaan artistik, Jagat Rasa juga mengajarkan pelajaran hidup sederhana yang tak terduga. “Pelajaran tak terduganya itu lebih ke budi pekerti sendiri,” kata Syifa dengan jujur. Pelajarannya? “Ketika kamu lagi motret atau apapun, sediakanlah minum!” Pengalamannya ‘standby‘ berjam-jam tanpa persiapan fisik yang memadai membuka matanya. “Ternyata motret tuh capek lho,” akunya, tertawa mengenang betapa tangan yang pegal dan stamina yang drop bisa mengganggu fokus mencari angle terbaik. Ini adalah pelajaran tentang merawat diri sendiri agar bisa menjaga tanggung jawab dengan baik.
Jika semua pengalaman itu dirangkum, Syifa menyimpulkannya dalam satu kalimat yang padat: “Capek, tapi seru.” Dua kata itu mewakili dua sisi koin yang sama. “Capek” adalah bayaran untuk kesiapan fisik yang kurang dan perjuangan teknis di belakang layar. “Seru” adalah buah dari kepekaan yang terasah, yang berujung pada kepuasan tak ternalar saat berhasil “mencuri” sebuah momen sempurna. “Senang aja, kayak ‘wah!’… momennya pun datang,” ujarnya.
Dengan demikian, Jagat Rasa telah meninggalkan warisan ganda. Selain sebagai pertunjukan yang memukau, acara ini menjadi bukti bahwa ruang belajar seorang calon pendidik dan seniman bahasa bisa hadir di mana saja bahkan di balik lensa kamera. Di sana, mereka belajar bahwa untuk mengabadikan sebuah “Jagat Rasa”, seseorang harus terlebih dahulu melatih kepekaan rasa dan kesiapan dirinya sendiri. Benar-benar, sebuah pembelajaran yang lebih dari sekadar jepretan.
Editor: Niken Awra Salsabila