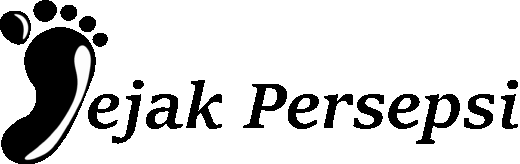Di sudut panggung Jagat Rasa, sebuah gerobak bertuliskan “Wedang Kacang” berdiri tanpa sorotan. Tidak mencolok, tidak mendominasi. Namun dari titik inilah pementasan Orang-Orang di Tikungan Jalan mulai bergerak.
Orang-orang singgah di tikungan itu, duduk sejenak, memesan wedang kacang. Minuman hangat menjadi alasan berhenti sebelum percakapan beralih ke hal yang lebih berat. Penjual wedang kacang melayani dengan tenang, lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Di tengah suasana itu, ia mengucapkan kalimat singkat, “Seorang gadis. Ia gila. Selalu saja menyeru bapaknya.” Saat seorang pelanggannya bertanya ketika ada suara teriakan ditengah malam yang sunyi, ucapan yang datar itu mengubah cara penonton memandang tikungan jalan. Dari sana tersirat bahwa tempat ini menyimpan cerita lama yang berulang, dan penjual wedang kacang mengetahuinya karena ia selalu ada di sana.
Tikungan jalan tidak sekadar latar, melainkan ruang sosial tempat berbagai kehidupan bersinggungan. Wedang kacang hadir sebagai bagian dari keseharian, bukan simbol besar. Penjualnya tidak terlibat konflik, tetapi mengetahui banyak hal dari peristiwa yang terus lewat.
Sudut pandang ini mencerminkan realitas masyarakat urban, di mana sosok kecil seperti pedagang kaki lima sering menjadi penonton dari perubahan sosial, melihat, mendengar, dan mengingat, tanpa pernah menjadi pusat cerita.
Pementasan ini tidak mengeksploitasi penjual wedang kacang. Ia tidak dikasihani atau didramatisasi berlebihan. Ia hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bekerja, menyampaikan secuil cerita, lalu kembali ke belakang panggung.
Pendekatan ini mengajak penonton menyadari keberadaan sosok yang sering terpinggirkan tanpa memaksanya menjadi tokoh utama.
Lewat Orang-Orang di Tikungan Jalan, Jagat Rasa menunjukkan bahwa cerita besar sering bersembunyi di pinggir panggung. Dari secangkir wedang kacang dan kalimat singkat yang ditinggalkan, penonton memahami bahwa tikungan jalan menyimpan ingatan yang jauh lebih panjang dari yang terlihat.
Editor: Fitria Anggi