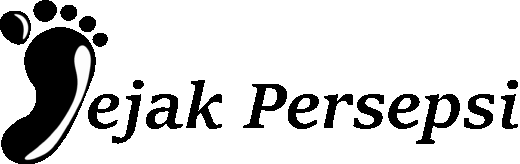PURWOKERTO — Rasanya aneh jika satu hari berlalu tanpa tugas, rapat, atau proyek yang harus diselesaikan. Bagi banyak mahasiswa, kata “sibuk” kini terdengar lebih bergengsi daripada “santai.” Di media sosial, unggahan tentang to-do list, meeting beruntun, atau jadwal padat sering dianggap tanda kesuksesan. Tak sedikit yang akhirnya merasa bersalah hanya karena mengambil waktu untuk beristirahat. Di tengah tekanan untuk selalu bergerak, muncul pertanyaan yang perlu kita renungkan: benarkah kita produktif, atau sebenarnya hanya terjebak dalam hustle culture?
Budaya hustle, yakni dorongan untuk terus bekerja dan beraktivitas tanpa henti, telah menyusup ke dunia mahasiswa dengan halus. Di balik semangat produktif itu, terselip tuntutan tidak tertulis bahwa waktu luang adalah bentuk kemalasan. Kita bangga saat hari-hari terasa penuh, tapi jarang bertanya, “Untuk apa aku melakukan semua ini?” Mahasiswa berlomba mengikuti banyak kepanitiaan, magang, dan lomba, padahal sebagian melakukannya bukan karena minat, melainkan takut ketinggalan dari teman seangkatan.
Media sosial pun memperkuat ilusi tersebut. Di TikTok dan Instagram, video bertema “productive day in my life” atau “how to manage your time” mengajarkan cara mengatur hidup yang efisien, tapi jarang mengingatkan pentingnya jeda. Kesibukan kemudian menjadi identitas baru: semakin padat jadwalmu, semakin dianggap kamu berhasil. Namun, di balik layar, banyak mahasiswa yang diam-diam kelelahan. Mereka bangun dengan rasa cemas, takut gagal, atau merasa tertinggal, bahkan saat sedang berprestasi. Inilah paradoks hustle culture: semakin keras kita bekerja, semakin sulit kita menemukan rasa cukup.
Kampus pun tanpa sadar ikut melestarikan budaya ini. Sistem yang menuntut mahasiswa aktif di segala bidang sering kali membuat batas antara semangat belajar dan beban psikis menjadi kabur. Mahasiswa dituntut berprestasi, berorganisasi, sekaligus menjaga nilai akademik. Namun, jarang ada ruang untuk benar-benar diam dan merenung tentang arah hidup atau kebahagiaan pribadi.
Padahal, seperti yang ditulis Henry Manampiring dalam buku Filosofi Teras (2018), “Menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko berujung pada kekecewaan.” Kalimat ini terasa sangat relevan bagi mahasiswa yang mengejar validasi melalui kesibukan. Kita sering kali mencari rasa puas dari pengakuan luar, entah dari teman, dosen, atau media sosial, padahal sumber kebahagiaan sejati justru ada dalam kendali diri sendiri.
Produktivitas sejati tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa besar nilai yang kita dapatkan dari setiap kegiatan itu. Istirahat bukan tanda malas, melainkan bagian dari proses tumbuh. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, menolak beberapa tawaran, atau memilih tidak sibuk setiap hari. Kita tidak diciptakan untuk berlari tanpa henti, tapi untuk hidup dengan ritme yang manusiawi.
Mungkin sudah saatnya kita menata ulang makna produktif. Bukan lagi tentang kerja tanpa henti, melainkan tentang keseimbangan antara ambisi dan kesehatan diri. Karena pada akhirnya, tidak ada gunanya menjadi mahasiswa yang aktif di mana-mana jika di dalam hati kita merasa kosong. Produktif boleh, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri di tengah kesibukan.
Editor: Iin Insyiroh