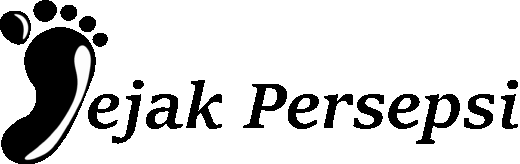Purwokerto—Belakangan ini, istilah cancel culture sering muncul di media sosial. Fenomena ini terjadi ketika seseorang baik publik figur maupun orang biasa diboikot atau diserang karena dianggap melakukan kesalahan, entah lewat ucapan atau tindakan. Awalnya, cancel culture muncul sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar setiap orang lebih berhati-hati. Tapi sayangnya, fenomena ini sering kali bergeser jadi ajang penghakiman tanpa proses yang adil.
Penelitian dari Universitas Islam Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa dampak cancel culture sangat bergantung pada konteksnya. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami Lutfi Agizal saat mempermasalahkan kata “anjay”, budaya pembatalan ini justru menutup ruang diskusi sehat. Banyak warganet langsung menghujat tanpa mau mendengar penjelasan. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya jadi tempat bertukar pikiran berubah menjadi arena saling serang.
Dampak cancel culture sendiri tidak hanya bersifat merugikan. Dalam situasi tertentu, tekanan publik dapat membantu mendorong penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus pelecehan atau kekerasan, tekanan publik di media sosial sering kali mendorong pihak berwenang untuk bertindak. Namun, ketika dilakukan tanpa bukti yang jelas atau hanya karena ikut-ikutan opini publik, budaya ini bisa melukai reputasi seseorang secara permanen.
Sebagai pengguna media sosial, pengguna media sosial perlu lebih bijak dalam menanggapi isu. Alih-alih langsung menghakimi, ada baiknya dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kritik tetap penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang menghormati. Dunia digital akan jadi tempat yang lebih sehat apabila masyarakat belajar berdialog, bukan saling menjatuhkan.
Editor: Zahra Jerolin Hanifah