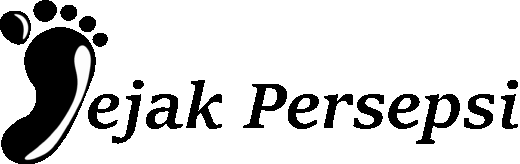Purwokerto — Saat budaya tradisi perlahan tergeser oleh arus digital dan tontonan instan, masih terdapat tokoh seniman yang tetap menyalakan blencong budaya, agar tidak padam. Ia adalah Arif Sudarsono atau dikenal sebagai Ki Arif Sudarsono, seorang dalang sekaligus pembuat wayang kulit asal Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang memandang wayang bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan ruang refleksi moral, serta spiritual bagi manusia modern.
Perjalanan Awal dan Kecintaan pada Wayang
Kecintaan-nya terhadap dunia wayang berawal sejak kecil. “Mulai suka wayang sejak smp, sekitar tahun 1980-an. Dulu istilahnya gebyak, atau latihan pentas kecil dengan gedebok pisang,” kenangnya. Beranjak dari hal tersebut, muncul keingintahuan terhadap dunia pedalangan, yang tumbuh menjadi panggilan hidup.
Tidak puas hanya menjadi dalang, Arif juga mempelajari seni dalam membuat wayang. “Saya hobi menggambar wayang. Awalnya dari kardus, lama-lama pakai kulit sapi, dan kerbau. Bukan untuk dijual, tapi karena memang cinta,” ujarnya. Proses penciptaan wayang baginya merupakan perjalanan spiritual, dan intelektual. Setiap tahap mulai dari merendam kulit selama 8 jam, menatah selama 2 minggu, hingga menyunggin selama 2 minggu, ia jalani dengan kesabaran, serta rasa hormat pada leluhur.
Kemampuan membuat wayang memberi keunggulan tersendiri dalam setiap pementasan. “Kalau dalang bisa membuat wayang, maka dia hafal semua detail busananya dari kepala hingga kaki. Kalau tidak bisa membuat, ya sering bawa catatan,” tuturnya. Ia lalu menjelaskan dengan rinci. “Ini semulian, ini kancing sabuk namanya badong. Ini garuda mungkur, artinya garuda yang menghadap ke belakang. Semua hal tersebut memiliki arti.”
Menurut-nya, seorang dalang yang juga perajin akan lebih memahami filosofi, dan anatomi wayang, sehingga setiap dialog yang diucapkan di panggung lahir dari pemahaman, bukan sekadar hafalan.

Kiprah dan Prestasi
Dalam kiprah-nya, Arif dikenal aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan, terutama peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia di Semarang. Dalam setiap sajang tersebut, ia menampilkan karya, dan kemampuan mendalangnya yang khas dengan gaya Banyumasan yang lugas tetapi sarat akan makna.
Ia juga pernah tampil di berbagai panggung bergengsi, di antaranya pementasan di hadapan Ketua MPR RI Amien Rais, serta peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto saat Ganjar Pranowo masih menjabat gubernur. Namun, di balik pencapaian itu, ia tetap sederhana dan reflektif. “Saya memang tidak sering ditanggap besar, tapi saya bahagia bisa tampil di hadapan tokoh-tokoh penting. Itu bentuk penghargaan bagi seni wayang sendiri,” ujarnya.
Kini, sang maestro fokus menekuni bidang keahliannya sebagai dalang sekaligus pembuat wayang kulit. Ia juga mengembangkan inovasi pertunjukan Wayang Santri Tiga Jaman, yang merupakan bentuk pementasan berdurasi tiga jam, dan kerap dibawakan dalam pengajian, serta kegiatan keagamaan. “Wayang Santri itu cara saya untuk membawa nilai moral, dan dakwah lewat budaya,” ujarnya.
Pandangan tentang Wayang dan Nilai Kehidupan
Baginya, wayang bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebagai cermin kehidupan. “Wayang itu tontonan sekaligus tuntunan. Dari Puntadewa kita belajar kebijaksanaan, dari Kresna kita belajar strategi, dan dari Bima kita belajar keberanian,” ungkapnya.
Meski sadar bahwa generasi muda kini kian menjauh dari dunia pewayangan, Arif tetap optimistis. “Sekarang harus pandai menarik minat penonton. Campur dengan campursari, pelawak, atau unsur modern, tapi nilai utamanya jangan hilang,” pesannya.
Sebagai seniman yang hidup di antara tradisi dan modernitas, Arif berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada slogan nguri-uri budaya. “Perlu pembinaan, pelatihan, dan regenerasi dalang muda. Wayang bukan hanya milik Solo dan Jogja, tapi juga Banyumas. Budaya ini milik bersama,” tegasnya.
Dalam setiap pementasan dan pahatan, Arif seolah menegaskan bahwa menjadi dalang bukan hanya menggerakkan boneka kulit di balik kelir, tetapi juga menghidupkan nilai kemanusiaan di tengah dunia yang kian kehilangan arah. “Selama blencong masih menyala,” katanya pelan, “nilai-nilai kita belum padam.”
Editor : Arsa Rahman Hidayatulloh