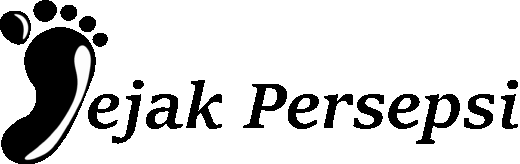Seorang mahasiswa duduk di perpustakaan dengan tumpukan buku dan catatan di atas meja (Foto: foto latar belakang gratis dari id.pngtree.com/)
Tidak semua kelelahan datang dengan suara. Sebagian hadir diam-diam, bersembunyi di balik jadwal padat, senyum tipis di ruang kelas, dan kalimat klise yang terdengar akrab di telinga mahasiswa “Capek itu biasa.”
Di lingkungan kampus, lelah sering kali tidak dianggap sebagai tanda bahaya, melainkan lencana kehormatan. Mahasiswa yang pulang paling malam, mengerjakan tugas sambil menahan kantuk, atau aktif di berbagai kegiatan justru dipuji sebagai sosok tangguh. Dalam budaya semacam ini, kuat berarti terus berjalan, meski tubuh dan pikiran sudah meminta berhenti.
Pagi hari di ruang kelas misalnya, banyak mahasiswa duduk dengan mata sembap dan konsentrasi yang terpecah. Semalam mereka begadang bukan untuk bersenang-senang, melainkan menyelesaikan tugas, laporan, atau pekerjaan paruh waktu. Ketika ditanya soal kondisi mereka, jawabannya hampir selalu sama, yaitu “Masih kuat.” Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kelelahan yang jarang diakui.
Bagi sebagian mahasiswa, lelah bukan lagi keluhan, melainkan rutinitas. Tuntutan akademik, tekanan untuk berprestasi, serta ekspektasi sosial agar selalu produktif membuat kelelahan seolah menjadi syarat tak tertulis untuk disebut “Mahasiswa yang aktif.” Ironisnya, semakin lelah seseorang, semakin besar pula apresiasi yang diterima dari lingkungan sekitar.
Media sosial turut memeperkuat budaya ini. Unggahan tentang begadang, tumpukan tugas, atau jadwal yang padat sering kali dibingkai sebagai konten motivasi. Kalimat seperti “Istirahat belakangan, yang penting tugas aman,” berulang kali muncul dan dikonsumsi tanpa dikritisi. Tanpa disadari, kelelahan tidak lagi dipandang sebagai kondisi yang perlu ditangani, malainkan sesuatu yang harus dibanggakan.
Namun, di balik narasi “Masih kuat” itu, ada konsekuensi yang jarang dibicarakan. Kelelahan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan konsentrasi, memicu stres, dan perlahan menggerus kesehatan mental. Sayangnya, banyak mahasiswa memilih diam. Mengeluh dianggap lemah, meminta jeda sering kali dipersepsikan sebagai ketidakmampuan mengatur waktu.
Tidak sedikit pula mahasiswa yang merasa bersalah ketika beristirahat. Waktu luang kerap diiringi rasa cemas, takut tertinggal, takut dianggap malas, atau takut tidak cukup berjuang. Dalam kondisi seperti ini, istirahat bukan lagi hak, melainkan kemewahan yang harus ‘dibayar’ dengan rasa bersalah.
Mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai aktivitas dan tanggung jawab secara bersamaan. Kondisi ini perlahan membentuk pola pikir bahwa kelelahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Akibatnya, ruang untuk mengenali batas diri kerap terpinggirkan, meskipun tidak pernah secara eksplisit diminta.
Normalisasi lelah pada akhirnya tidak melahirkan generasi tangguh, melainkan generasi yang terbiasa menekan perasaan. Di titik tertentu, yang rusak bukan hanya tubuh, tetapi juga relasi dengan diri sendiri, ketika lelah tidak lagi dikenali, apalagi dirawat.
Mungkin sudah saatnya budaya “Masih kuat” ditinjau ulang. Menjadi kuat tidak selalu berarti bertahan tanpa jeda. Terkadang, keberanian justru hadir ketika seseorang berani mengakui bahwa ia lelah dan memilih untuk berhenti sejenak.