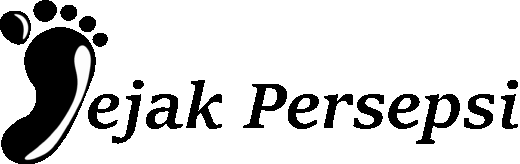Sumber: Dokumentasi Pribadi
Purwokerto – Seperti embun yang jatuh dini hari, fenomena self-diagnose perlahan tumbuh menjadi arus besar di media sosial TikTok. Di linimasa yang bergerak cepat, banyak remaja dan mahasiswa dari generasi Z mulai menyimpulkan kondisi kesehatan mentalnya hanya dari video berdurasi 15 hingga 60 detik.
Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat. Berdasarkan laporan platform We Are Social, lebih dari 106 juta pengguna TikTok di Indonesia didominasi usia 18–24 tahun, rentang usia yang kini dianggap paling rentan mencari identitas melalui media sosial.
Fenomena ini terjadi karena rendahnya literasi kesehatan mental pada remaja. Pengguna TikTok cenderung langsung menerima informasi psikologi atau mental health tanpa proses verifikasi sumber. Kolom komentar dipenuhi pengakuan diri, seperti: “aku anxiety”, “gw depresi”, “kayaknya itu aku”.
Menurut pakar psikolinguistik yaitu Wahya, fenomena self-diagnose ini bergantung pada kepercayaan dirinya sendiri. Jika mental seseorang dalam keadaan lemah, pernyataan-pernyataan konten berbau sosialisasi kesehatan mental itu dapat memengaruhi kondisi mentalnya. Tetapi, jika seseorang itu dalam keadaan sadar sepenuhnya maka pernyataan-pernyataan dalam konten itu seharusnya dipertanyakan dan harus diverifikasi lagi benar atau salahnya. Seringkali konten kreator kesehatan tidak dilakukan oleh profesional, hanya orang-orang tertentu yang mungkin ingin mengejar rating saja atau click-bait.
Saya melihat fenomena ini muncul bukan hanya karena TikTok berisi banjir informasi, tetapi karena generasi ini tumbuh dengan kebutuhan validasi yang tidak pernah selesai. Label seperti anxiety, overthinking, atau introvert menjadi semacam identitas digital yang siap ditempel di bio, komentar, atau caption. Di sisi lain, saya tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua yang melakukan self-diagnosis bertujuan mencari sensasi atau tren. Banyak dari mereka justru mencari bahasa untuk menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak bisa mereka pahami. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika pengetahuan yang seharusnya dikonfirmasi tenaga profesional, justru berhenti pada asumsi yang dibuat oleh algoritma media sosial.
Rumah Sakit Elizabeth Situbondo melalui laman edukasinya memberikan peringatan: “Meskipun self-diagnose dapat menjadi langkah awal dalam memahami kesehatan mental, penting bagi generasi Z untuk menyadari risiko-risiko yang menyertainya. Konsultasi dengan profesional kesehatan mental tetap menjadi langkah terbaik untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Edukasi tentang kesehatan mental dan penyaringan informasi dari sumber terpercaya sangat penting untuk membantu generasi ini dalam menavigasi isu-isu kesehatan mental dengan lebih baik.” Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa diagnosis medis bukan ruang opini, melainkan ruang ilmiah yang membutuhkan prosedur, wawancara klinis, dan evaluasi.
Pada akhirnya, self-diagnose TikTok adalah fenomena pencarian identitas yang terjadi ketika generasi modern lebih sering berbicara dengan layar dibanding dirinya sendiri. Ada rasa ingin dimengerti, ada rasa ingin menemukan jawaban, tetapi jawaban yang terburu-buru hanya akan menjadi luka yang tumbuh dalam senyap. Karena sebelum menyebut diri anxiety, ADHD, atau depression barangkali yang paling dibutuhkan bukan label, melainkan keberanian untuk bertanya pada ahli yang memahami tubuh, pikiran, dan hati manusia.
Editor: Aulia Putri Sabrina