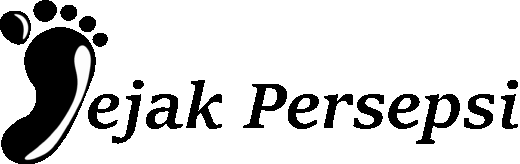Gagasan bahwa calon guru harus dibiasakan mendesain kurikulum sendiri berangkat dari kesadaran mendasar tentang perubahan lanskap pembelajaran abad ke-21, terutama ketika pendidikan mulai mengadopsi pendekatan deep learning sebagai orientasi pedagogis. Deep learning, dalam makna pedagogisnya, bukan sekadar penggunaan teknologi canggih atau kecerdasan buatan, melainkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, keterkaitan antarkonsep, refleksi kritis, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas, adaptivitas, dan sensitivitas guru terhadap dinamika kelasnya sendiri. Dalam kerangka tersebut, guru tidak lagi dapat diposisikan sebagai pelaksana kurikulum yang pasif, melainkan sebagai desainer pengalaman belajar. Namun, realitas pendidikan kita masih menempatkan calon guru sebagai pengguna kurikulum yang “sudah jadi”, yang tinggal diterapkan tanpa ruang tafsir dan kreasi yang memadai. Akibatnya, ketika mereka dihadapkan pada tuntutan deep learning, banyak guru mengalami kegamangan karena tidak memiliki otoritas pedagogis untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata siswanya. Oleh karena itu, membiasakan calon guru mendesain kurikulum sendiri sejak masa pendidikan awal keguruan bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan kebutuhan epistemologis untuk menjawab tantangan pembelajaran bermakna.
Untuk menjawab tuntutan deep learning secara utuh, guru harus memiliki otoritas terhadap kelasnya sendiri, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Otoritas ini bukan dimaknai sebagai kekuasaan absolut tanpa kontrol, melainkan sebagai ruang profesional untuk mengambil keputusan pedagogis berdasarkan pemahaman kontekstual terhadap siswa. Deep learning tidak mungkin tumbuh dalam kelas yang seluruh prosesnya dikendalikan oleh dokumen kurikulum yang kaku dan seragam. Setiap kelas memiliki ekologi belajar yang unik: latar belakang sosial-budaya siswa, kemampuan awal, minat, dinamika relasi, bahkan kondisi psikologis kolektif yang berubah dari waktu ke waktu. Guru adalah aktor yang paling dekat dengan realitas tersebut, sehingga merekalah yang paling kompeten untuk menyesuaikan arah pembelajaran. Namun, ketika guru tidak dilatih untuk membaca kurikulum secara kritis dan mengembangkannya secara kreatif, otoritas pedagogis itu menjadi tumpul. Guru cenderung merasa “tidak berwenang” mengubah tujuan, materi, atau strategi pembelajaran, meskipun mereka sadar bahwa pendekatan yang digunakan tidak efektif. Dalam konteks ini, membiasakan calon guru mendesain kurikulum sendiri merupakan proses pembentukan kesadaran profesional bahwa guru bukan sekadar operator sistem, tetapi intelektual praktis yang memiliki legitimasi untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan konteks kelasnya.
Masalahnya, dalam praktik pendidikan sehari-hari, guru sering kali tidak memiliki kuasa yang cukup untuk memperbaiki sistem pembelajaran, meskipun merekalah yang paling memahami persoalan di lapangan. Banyak guru terjebak dalam struktur birokrasi pendidikan yang hierarkis, di mana kebijakan kurikulum, penilaian, dan administrasi ditentukan secara top-down. Guru dituntut patuh pada target capaian, format perangkat ajar, dan skema evaluasi yang sudah ditetapkan, tanpa ruang dialog yang memadai. Dalam situasi seperti ini, inisiatif guru untuk melakukan inovasi sering kali dipandang sebagai penyimpangan, bukan sebagai bentuk profesionalisme. Akibatnya, guru belajar untuk “aman” dengan mengikuti aturan, bukan untuk berpikir kritis dan reflektif. Kondisi ini berdampak serius pada kualitas pembelajaran, karena sistem yang tidak adaptif akan selalu tertinggal dari kebutuhan nyata siswa. Ketika calon guru dibesarkan dalam kultur kepatuhan semata, mereka akan mewarisi pola pikir bahwa tugas guru hanyalah menjalankan kurikulum, bukan mengembangkannya. Oleh karena itu, pembiasaan mendesain kurikulum sendiri sejak awal pendidikan calon guru menjadi strategi penting untuk memutus mata rantai ketidakberdayaan pedagogis yang selama ini menghambat transformasi pembelajaran.
Membiasakan guru untuk membuat kurikulum sendiri tidak berarti meniadakan kurikulum nasional atau standar kompetensi yang telah ditetapkan negara. Sebaliknya, hal ini justru memperkuat fungsi kurikulum nasional sebagai kerangka acuan, bukan sebagai skrip yang harus diikuti secara literal. Calon guru perlu dilatih untuk memahami kurikulum sebagai dokumen hidup yang dapat ditafsirkan, disesuaikan, dan dikembangkan sesuai dengan konteks. Dalam praktiknya, banyak guru hanya mengenal kurikulum pada level administratif—kompetensi inti, kompetensi dasar, atau capaian pembelajaran—tanpa benar-benar memahami logika konseptual di baliknya. Akibatnya, kurikulum diperlakukan sebagai daftar kewajiban, bukan sebagai peta jalan pembelajaran. Dengan membiasakan calon guru menyusun kurikulum sendiri, mereka akan belajar membaca kebutuhan belajar siswa, merumuskan tujuan pembelajaran yang bermakna, memilih materi yang relevan, serta merancang pengalaman belajar yang kontekstual. Proses ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogis, tetapi juga membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap pembelajaran yang mereka kelola.
Pertanyaan penting berikutnya adalah: apa yang harus dilakukan guru dalam proses designing kurikulum tersebut? Langkah pertama yang fundamental adalah melakukan analisis konteks secara mendalam. Guru perlu memahami siapa siswanya, bagaimana latar belakang sosial dan budaya mereka, apa kebutuhan dan minat belajarnya, serta tantangan apa yang mereka hadapi. Analisis konteks ini menjadi dasar bagi seluruh keputusan kurikuler berikutnya. Tanpa pemahaman konteks, kurikulum akan menjadi abstrak dan jauh dari realitas siswa. Langkah kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi berpikir, sikap, dan keterampilan hidup. Dalam pendekatan deep learning, tujuan pembelajaran harus dirancang untuk mendorong siswa memahami konsep secara mendalam, mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman, serta merefleksikan proses belajarnya. Guru perlu dilatih untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat terbuka, fleksibel, dan kontekstual, bukan sekadar menyalin rumusan dari dokumen resmi.
Langkah selanjutnya dalam designing kurikulum adalah memilih dan mengorganisasi materi pembelajaran secara bermakna. Guru perlu memahami bahwa materi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan materi harus didasarkan pada relevansi, kebermaknaan, dan potensi eksplorasi konsep secara mendalam. Dalam konteks ini, guru juga perlu diberi ruang untuk mengintegrasikan muatan lokal, isu-isu aktual, dan pengalaman hidup siswa ke dalam kurikulum. Selain itu, guru harus merancang strategi pembelajaran yang selaras dengan prinsip deep learning, seperti pembelajaran berbasis masalah, proyek, inkuiri, dan refleksi. Strategi-strategi ini menuntut perencanaan yang matang dan fleksibel, karena guru harus siap menyesuaikan arah pembelajaran berdasarkan respons siswa. Tanpa pengalaman mendesain kurikulum sendiri, guru akan kesulitan mengelola kompleksitas pembelajaran semacam ini dan cenderung kembali pada metode ceramah yang aman tetapi dangkal.
Aspek penting lain dalam designing kurikulum adalah perencanaan asesmen yang selaras dengan tujuan dan proses pembelajaran. Guru perlu dibiasakan untuk merancang asesmen sebagai bagian integral dari pembelajaran, bukan sebagai aktivitas terpisah di akhir proses. Dalam pendekatan deep learning, asesmen seharusnya bersifat formatif, reflektif, dan autentik, sehingga mampu memberikan gambaran utuh tentang perkembangan belajar siswa. Guru perlu dilatih untuk menyusun instrumen asesmen yang valid, reliabel, dan kontekstual, serta mampu memanfaatkan hasil asesmen untuk memperbaiki pembelajaran. Proses ini menuntut kemampuan analitis dan reflektif yang tidak dapat tumbuh jika guru hanya mengandalkan instrumen asesmen yang sudah jadi. Dengan membiasakan calon guru mendesain kurikulum sendiri, termasuk asesmennya, mereka akan belajar melihat keterkaitan antara tujuan, proses, dan evaluasi pembelajaran secara sistemik.
Pada akhirnya, membiasakan calon guru mendesain kurikulum sendiri adalah investasi jangka panjang untuk membangun profesionalisme guru yang otonom, reflektif, dan adaptif. Dalam konteks pendidikan yang terus berubah, guru tidak bisa terus bergantung pada sistem yang sering kali lambat merespons kebutuhan lapangan. Guru yang memiliki pengalaman dan kepercayaan diri dalam mendesain kurikulum akan lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran, termasuk tuntutan deep learning yang kompleks. Mereka tidak hanya mampu menjalankan kebijakan, tetapi juga mampu mengkritisi dan memperbaikinya dari dalam kelas. Dengan demikian, kelas tidak lagi menjadi ruang implementasi kebijakan semata, melainkan laboratorium pedagogis tempat guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan. Jika pendidikan ingin benar-benar bertransformasi, maka calon guru harus diperlakukan sebagai perancang kurikulum sejak awal, bukan sekadar sebagai pelaksana yang patuh.