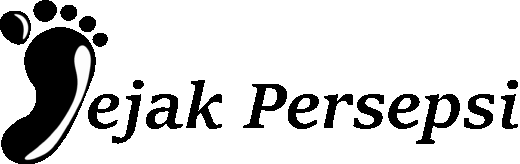Banyuwangi — Nama Sofyan Ramadani Halim mungkin masih terbilang baru di dunia industri farmasi, tetapi semangat dan pandangannya mengenai profesi apoteker patut diapresiasi. Lulusan S1 Farmasi Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2024 ini kini telah resmi menyandang gelar Apoteker lulusan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) tahun 2025. Setelah menjalani sumpah apoteker, Sofyan mantap menapaki kariernya di dunia industri farmasi bidang yang menurutnya menuntut ilmu tinggi, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral yang besar
Ketika ditanya bagaimana awal ketertarikannya pada bidang industri farmasi, Sofyan menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. Baginya, minat itu bukan datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan seiring proses belajar dan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Diponegoro.
“Ketertarikan saya muncul saat kuliah sarjana di Undip. Awalnya hanya penasaran bagaimana obat dibuat dan dikontrol. Lama-kelamaan saya menyadari bahwa pembuatan obat merupakan proses yang kompleks serta menuntut tanggung jawab besar,” ujarnya dengan nada reflektif.
Rasa ingin tahunya yang besar membuat Sofyan semakin antusias mendalami setiap mata kuliah yang berhubungan dengan industri farmasi. Ia tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mulai menaruh perhatian pada regulasi, standar produksi, hingga prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang menjadi fondasi utama dalam menjaga mutu produk farmasi di Indonesia.
Pengalaman magang profesi di PT Promedrahardjo Farmasi Industri, Sukabumi, menjadi titik balik yang menguatkan pilihannya. Di sana, Sofyan untuk pertama kalinya melihat langsung bagaimana proses pembuatan obat dilakukan dari tahap awal hingga produk siap dipasarkan. Setiap langkah, mulai dari penimbangan bahan baku hingga pengujian akhir di laboratorium, dijalankan dengan disiplin dan pengawasan ketat.
“Saya melihat langsung bagaimana proses pembuatan obat berlangsung. Semuanya harus sesuai prosedur dan diawasi ketat. Saat itu, saya merasa bangga karena pekerjaan apoteker benar-benar berdampak besar bagi banyak orang,” kenangnya.
Pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran mendalam dalam dirinya bahwa menjadi apoteker di industri bukan sekadar bekerja di balik meja laboratorium. Lebih dari itu, profesi ini menuntut ketelitian, integritas, dan dedikasi tinggi untuk memastikan setiap obat yang sampai ke tangan pasien benar-benar aman, bermutu, dan bermanfaat.
Kini, setelah resmi menyandang gelar apoteker dan mengucap sumpah profesi, Sofyan memiliki kewenangan penuh dalam praktik kefarmasian, termasuk dalam meracik obat, melakukan pengawasan mutu, serta memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
“Ya, sekarang saya sudah dapat meracik obat sesuai ketentuan serta melakukan pengujian berdasarkan standar yang berlaku. Namun bagi saya, meracik obat bukan sekadar mencampurkan bahan. Itu adalah tanggung jawab besar untuk memastikan obat aman dan efektif bagi pasien,” tegasnya.
Bagi Sofyan, profesi apoteker di dunia industri farmasi bukan hanya tentang menghasilkan obat, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, di balik setiap tablet dan kapsul yang beredar, terdapat kerja keras, ketelitian, serta tanggung jawab moral seorang apoteker untuk menjamin keselamatan dan kesehatan banyak orang.
Menurut Sofyan, hal yang paling menantang dalam dunia industri farmasi bukan terletak pada alat, bahan, atau teknologi yang digunakan, melainkan pada regulasi dan standar ketat yang harus dijalankan secara konsisten setiap hari. Di balik kemasan obat yang tampak sederhana, terdapat proses panjang yang diatur secara rinci melalui sistem yang disebut CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).
“CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik merupakan pedoman utama bagi industri farmasi. Setiap langkah, alat, bahkan suhu ruangan diatur secara ketat, dan semuanya harus dipatuhi,” jelasnya dengan nada serius.
CPOB, lanjutnya, bukan hanya kumpulan aturan teknis, tetapi juga cerminan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Setiap personel di industri farmasi harus memahami dan menerapkan standar tersebut dalam setiap kegiatan, mulai dari perancangan fasilitas, pengolahan bahan baku, hingga pengemasan dan penyimpanan produk jadi.
Ia menambahkan bahwa standar yang diterapkan tidak bersifat seragam untuk semua produk. Ada perbedaan mendasar antara pembuatan produk steril dan nonsteril yang menuntut kehati-hatian ekstra.
“Untuk produk steril, seperti injeksi atau obat tetes mata, area produksinya harus benar-benar bersih dan bebas dari mikroorganisme. Setiap partikel udara, tekanan ruangan, hingga pergerakan operator harus dikontrol. Sementara itu, produk nonsteril memang memiliki batas toleransi tertentu, tetapi tetap memerlukan kontrol ketat agar tidak terjadi kontaminasi,” terangnya.
Sofyan mengakui bahwa menerapkan CPOB secara penuh memang bukan hal yang mudah. Diperlukan koordinasi lintas divisi, ketelitian tinggi, serta komitmen dari seluruh tim produksi, analis, dan pengawas mutu. Ia menyebut bahwa dalam praktiknya, tantangan terbesar justru datang dari menjaga konsistensi penerapan standar tersebut dari hari ke hari.
“Kadang orang berpikir tantangan terbesar ada pada mesin atau bahan, padahal yang paling sulit adalah menjaga kepatuhan. CPOB bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Jika ada satu tahapan saja yang dilanggar, risikonya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan manusia,” tegasnya.
Bagi Sofyan, kepatuhan terhadap CPOB bukan sekadar tuntutan administratif atau formalitas untuk memenuhi inspeksi BPOM, melainkan bentuk tanggung jawab moral seorang apoteker terhadap masyarakat. Setiap obat yang lolos dari lini produksi membawa konsekuensi besar bagi keselamatan pasien, dan itu berarti tidak ada ruang untuk kesalahan.
“Hal inilah yang membuat kami di industri harus bekerja dengan sangat hati-hati. Bukan karena takut pada regulasi, tetapi karena kami sadar bahwa di balik setiap tablet dan ampul, ada kehidupan manusia yang bergantung pada mutu dan keamanan obat tersebut,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sofyan mengamati adanya perubahan besar pada pola pikir masyarakat terhadap kesehatan.
“Sekarang masyarakat lebih sadar pentingnya hidup sehat. Permintaan obat dan suplemen meningkat setiap tahun,” ujarnya. “Orang tidak lagi menunggu sakit untuk mencari obat, melainkan mulai menjaga kesehatan dengan mengonsumsi suplemen, vitamin, dan menjalani gaya hidup sehat.”
Menurutnya, tren tersebut mendorong industri farmasi untuk terus berkembang, namun juga membawa tanggung jawab yang lebih besar.
“Ketika permintaan meningkat, industri harus mampu memproduksi dalam jumlah besar tanpa menurunkan kualitas. Di sinilah peran apoteker menjadi sangat penting.”
Ketika ditanya mengapa peran apoteker di industri farmasi tidak dapat digantikan oleh profesi lain, Sofyan Ramadani Halim menjawab lugas tanpa keraguan sedikit pun. Baginya, posisi apoteker dalam dunia farmasi bukan sekadar pelengkap, melainkan poros utama yang memastikan setiap obat aman, bermutu, dan efektif sebelum sampai ke tangan masyarakat.
“Apoteker menguasai ilmu serta standar bagaimana obat seharusnya dibuat. Kami memahami dosis yang aman, interaksi bahan, hingga cara menjaga stabilitas produk,” jelasnya.
Ia kemudian menerangkan bahwa pengetahuan yang dimiliki apoteker tidak hanya terbatas pada sisi teoritis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab praktis yang luas — mulai dari perancangan formula, proses produksi, hingga penjaminan mutu. Dalam setiap tahapan tersebut, kehadiran apoteker menjadi kunci utama agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).
Namun, menurut Sofyan, keunikan peran apoteker tidak berhenti di situ. Profesi ini juga memiliki kemampuan untuk menjembatani komunikasi antarbagian di industri farmasi.
“Apoteker di industri harus mampu berkoordinasi dengan analis, operator, distributor, hingga apoteker di rumah sakit dan apotek. Semua pihak itu saling terhubung untuk memastikan mutu obat tetap terjaga,” tuturnya.
Kemampuan koordinatif tersebut membuat apoteker menjadi penghubung strategis antara proses produksi dan pelayanan kesehatan di lapangan. Mereka tidak hanya berbicara dengan data atau mesin, tetapi juga dengan manusia memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami tujuan bersama: menghasilkan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Lebih dari sekadar tenaga teknis, Sofyan memandang profesi apoteker sebagai penjaga moral dalam industri yang berbasis pada kepercayaan publik. Dalam setiap dosis dan setiap batch obat yang diproduksi, terdapat nilai etika yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau efisiensi.
“Bagi saya, profesi apoteker bukan hanya soal ilmu pengetahuan, melainkan juga tentang etika dan tanggung jawab moral. Setiap obat yang keluar dari pabrik harus benar-benar aman. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan,” tegasnya.
Baginya, apoteker bukan sekadar seseorang yang memahami senyawa kimia, melainkan sosok yang berdiri di antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Dalam setiap keputusan yang diambil, selalu ada kesadaran bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi perusahaan, tetapi juga keselamatan pasien yang mempercayakan hidupnya pada hasil kerja mereka.
“Selama masih ada manusia yang membutuhkan obat untuk sembuh, apoteker akan tetap dibutuhkan. Karena pada akhirnya, obat bukan hanya hasil reaksi kimia, tetapi hasil dari niat baik, pengetahuan, dan tanggung jawab seorang apoteker,” pungkasnya dengan senyum tenang.
Dunia industri farmasi tentu tidak lepas dari orientasi bisnis. Namun, Sofyan menegaskan bahwa aspek etika harus tetap menjadi prioritas utama.
“Farmasi memang perlu memperhatikan biaya produksi dan efisiensi, tetapi etika tidak boleh dikorbankan. Semua proses harus tetap mengikuti standar CPOB dan berada di bawah pengawasan BPOM,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa keseimbangan antara bisnis dan etika merupakan fondasi keberlanjutan industri.
“Jika hanya mengejar keuntungan, keselamatan pasien bisa terabaikan. Namun, apabila berpegang pada etika, kepercayaan masyarakat akan menjadi modal terbesar bagi industri untuk bertahan.”
Dalam dunia industri, tekanan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sofyan menjelaskan bahwa setiap tahap produksi memiliki tantangan tersendiri.
“Tekanan paling tinggi biasanya muncul ketika hasil produksi tidak sesuai standar. Kami harus segera mencari tahu letak kesalahannya, apakah pada bahan, alat, atau prosesnya. Di situ pentingnya kerja sama antara apoteker, analis, dan operator,” terangnya.
Proses Quality Control (QC), menurutnya, menjadi jantung pengawasan mutu.
“QC dilakukan oleh apoteker dengan bantuan analis. Semua hasil pengujian harus dicatat, lalu direviu oleh apoteker Quality Assurance (QA). Laporan tersebut nantinya dapat diperiksa kembali oleh BPOM,” jelasnya.
Bagi Sofyan, sistem kerja berlapis ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya kolektif untuk memastikan tidak ada obat cacat yang sampai ke tangan masyarakat.
Sofyan mengakui bahwa dunia industri sering menuntut efisiensi dan pencapaian target. Namun, baginya, idealisme ilmiah harus tetap dijaga.
“Idealisme ilmiah merupakan kompas utama kami. Obat bukan barang dagangan biasa, tetapi hasil riset yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan manusia. Walaupun target tinggi, prinsip keilmuan dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas.”
Ia menambahkan bahwa sumpah apoteker yang telah diucapkan menjadi pengingat moral dalam bekerja.
“Dalam sumpah apoteker, kami berjanji untuk mengutamakan keselamatan manusia di atas kepentingan apa pun. Sumpah itu bukan seremonial, tetapi prinsip hidup yang harus dipegang selamanya.”
Sofyan menilai bahwa masa depan industri farmasi Indonesia berada pada penguatan riset dan pengembangan (R&D).
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika riset dikembangkan secara serius, kita bisa mandiri dalam pembuatan obat,” ujarnya dengan optimisme.
Menurutnya, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pasar bagi obat luar negeri, melainkan juga produsen dengan inovasi sendiri.
“Banyak bahan herbal yang bisa dikembangkan menjadi obat modern. Jika riset diperkuat, industri farmasi nasional dapat bersaing secara global.”
Menariknya, Sofyan mengaku bahwa ide-ide inovatif sering kali muncul secara spontan.
“Kadang ide muncul saat diskusi santai dengan sejawat. Dari situ, bisa berkembang menjadi riset kecil yang kemudian diuji coba. Kreativitas tidak selalu lahir di laboratorium.”
Sofyan menjelaskan bahwa proses untuk menjamin keamanan obat tidak berhenti pada tahap produksi.
“Pertama, obat harus dibuat sesuai standar CPOB. Kedua, hasil produksi diuji secara menyeluruh oleh QC dan direviu oleh QA. Ketiga, laporan pengujian dikirim ke BPOM untuk diverifikasi. Semua proses itu memastikan obat yang beredar benar-benar aman.”
Selain itu, pengawasan tetap dilakukan hingga tahap distribusi.
“Apoteker bertanggung jawab mengontrol penyimpanan, suhu, kelembapan, dan kondisi pengiriman. Tujuannya agar obat tetap stabil dan mutu terjaga hingga sampai ke tangan pasien.”
Ketika ditanya mengenai momen paling membanggakan dalam perjalanan kariernya, Sofyan Ramadani Halim tersenyum tipis, seolah mengingat kembali hari-hari penuh kesibukan di ruang produksi. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menarik napas sebentar sebelum berbicara dengan nada tenang namun penuh makna.
“Saya paling bangga saat pertama kali mengawasi proses produksi dan melihat obat yang kami hasilkan lolos uji mutu. Rasanya luar biasa mengetahui bahwa kerja keras tim bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Sofyan, momen itu bukan hanya tentang keberhasilan teknis, melainkan juga simbol dari tanggung jawab besar yang dipikul seorang apoteker di industri farmasi. Ia melihat sendiri bagaimana setiap tahap produksi—mulai dari persiapan bahan baku, proses pencampuran, hingga pengujian akhir—memerlukan kerja sama, ketelitian, dan komitmen yang tinggi dari semua pihak.
“Saya belajar bahwa keberhasilan dalam industri farmasi tidak pernah dicapai sendirian. Ada analis, operator, dan sesama apoteker yang saling berperan. Semua punya tanggung jawab masing-masing untuk memastikan mutu obat benar-benar terjamin,” jelasnya.
Pengalaman itu menjadi titik penting yang mempertegas pandangannya terhadap profesi apoteker. Bagi Sofyan, menjadi apoteker bukan hanya tentang memahami kimia, formula, atau alat laboratorium, melainkan tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap obat yang mereka konsumsi.
“Sekarang saya sudah bisa meracik obat, melakukan pengujian, dan memastikan kualitasnya. Namun, yang lebih penting dari kemampuan itu adalah rasa tanggung jawab dan kehati-hatian,” katanya dengan nada tegas namun rendah hati.
Sofyan menyadari bahwa di balik setiap obat yang diproduksi, terdapat harapan banyak orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Itulah yang membuatnya merasa bangga sekaligus terpanggil untuk terus berkontribusi di dunia farmasi. Baginya, profesi apoteker bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga bentuk pengabdian dan amanah kemanusiaan
Menutup perbincangan, Sofyan Ramadani Halim menyampaikan harapannya bagi masa depan industri farmasi Indonesia. Suaranya terdengar mantap, namun tetap penuh keyakinan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.
“Saya ingin melihat Indonesia mandiri dalam riset dan tidak bergantung pada impor bahan baku. Kita memiliki potensi besar, hanya perlu dukungan kebijakan dan kolaborasi yang lebih kuat antara akademisi dan industri,” ujarnya.
Bagi Sofyan, kemandirian farmasi nasional bukan hanya tentang kemampuan memproduksi obat, melainkan juga tentang kedaulatan ilmu dan teknologi. Ia percaya bahwa dengan sinergi antara pendidikan tinggi, riset, dan sektor industri, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara lain dalam pengembangan obat dan inovasi kesehatan.
Di akhir pembicaraan, ia tidak lupa menyampaikan pesan sederhana namun bermakna bagi para mahasiswa farmasi yang masih menempuh pendidikan.
“Nikmati setiap prosesnya. Dunia industri memang menantang, tetapi di sanalah ilmu farmasi benar-benar bermanfaat bagi kehidupan banyak orang,” pesannya.
Bagi Sofyan, menjadi apoteker bukan sekadar gelar profesi, melainkan bentuk pengabdian dan komitmen untuk terus menjaga mutu, keamanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap obat yang mereka gunakan. Kini, setelah resmi menyandang gelar apoteker, ia siap melangkah lebih jauh untuk memberikan kontribusi nyata di dunia industri farmasi.
“Menjadi apoteker bukan hanya tentang formula, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan. Obat yang kita buat dapat menyelamatkan nyawa, dan itulah alasan saya mencintai profesi ini,” pungkasnya dengan senyum hangat.
Ucapan itu menutup percakapan dengan kesan mendalam. Dari kata-kata Sofyan tergambar jelas bahwa di balik ruang-ruang produksi yang penuh mesin dan instrumen kimia, ada hati da n niat tulus seorang apoteker yang bekerja demi kehidupan banyak orang. Sebuah dedikasi yang tak hanya diracik dengan ilmu, tetapi juga dengan nurani.
Editor : Satrio Wijaya