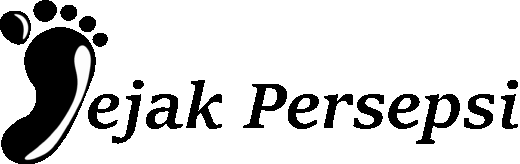Purwokerto — Beberapa tahun terakhir, kita melihat sesuatu yang tidak wajar tapi makin terasa normal, salah satunya adalah anak-anak remaja bahkan yang baru menginjak bangku SMP tampil selayaknya orang dewasa. Make up tebal, gaya pacaran yang intens, membuat konten “relationship goals”, dan tampilan dewasa yang dipoles rapi untuk media sosial. Sekilas terlihat lucu, tetapi lama-lama terasa mengkhawatirkan. Karena ketika kedewasaan tersebut dijadikan kostum, banyak yang mencoba memakainya sebelum mereka benar-benar siap.
Fenomena ini tidak hanya soal dandanan atau gaya hidup, tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius, termasuk meningkatnya kasus bullying dan kekerasan di usia yang seharusnya masih sibuk menemukan jati diri. Baru-baru ini, kita melihat kasus anak laki-laki membunuh temannya hanya karena permasalahan jalan dengan pacar orang. Tragis, absurd, sekaligus sangat menggambarkan betapa tipisnya batas antara “ingin terlihat dewasa” dan “tidak punya kapasitas emosional untuk mengelolanya.”
Yang menarik adalah bagaimana remaja sekarang menganggap pacaran sebagai syarat kematangan sosial. Seolah jika tidak punya pasangan, maka identitasnya belum lengkap. Pada waktu yang sama, emosi mereka masih labil, frontal, impulsif, dan mudah meledak. Kombinasi dua hal ini berbahaya karena memiliki rasa ingin diakui yang tinggi, tetapi kemampuan menyelesaikan konflik masih rendah. Jadilah drama yang mestinya hanya ada di sinetron, muncul di kehidupan nyata anak-anak yang bahkan belum selesai belajar mengatur perasaan sendiri.
Dan ironisnya, setiap kasus seperti ini kolom komentar dipenuhi nostalgia generasi milenial dan Gen Z. Mereka mengatakan bahwa di saat umur segitu, mereka masih main kelereng, berimajinasi menjadi Kamen Rider, atau bangga jika berhasil memenangkan permainan gasing di depan rumah. Mereka tidak pusing memikirkan “status hubungan”, apalagi mempertaruhkan harga diri demi seseorang yang bahkan belum bisa memutuskan ingin makan apa. Kontras ini membuat fenomena sekarang terasa semakin janggal: sejak kapan anak-anak harus memikul urusan orang dewasa?
Sebagian orang mungkin bertanya: “Tapi kan mereka sendiri yang mau pacaran, mau dandan, mau tampil dewasa?”
Iya, mereka merasa mau. Tetapi keinginan itu lahir dari lingkungan yang membombardir mereka sejak usia dini. Media sosial dipenuhi dengan narasi kedewasaan seperti pasangan muda yang tampil serasi, anak SMP yang viral karena makeup flawless, dan konten percintaan yang dirancang untuk menarik perhatian. Algoritma mendorong apa yang paling mudah mengikat emosi, kedewasaan estetis adalah salah satunya. Jadilah anak-anak yang belum selesai tumbuh, tetapi tampil seperti orang dewasa.
Masalahnya, kedewasaan itu hanya tampilan dari luar. Secara psikologis, mereka masih anak-anak yang butuh bimbingan, struktur, dan ruang untuk belajar. Ketika mereka meminjam atribut orang dewasa tanpa kemampuan emosional yang menyertainya, muncul gesekan besar berupa cemburu yang berlebihan, kompetisi status, tekanan sosial, hingga tindak kekerasan yang berawal dari rasa ingin mempertahankan harga diri yang sebenarnya rapuh.
Fenomena ini tidak bisa disederhanakan sebagai “nakal” atau “terlalu bebas.” Ini cerminan zaman yang membuat anak-anak tumbuh lebih cepat secara visual, tetapi tidak diberi kesempatan tumbuh secara emosional. Kedewasaan menjadi sesuatu yang mereka tiru, bukan jalani. Imitasi itu sering berakhir dengan luka, baik untuk mereka sendiri maupun orang di sekitar mereka.
Pada akhirnya, kasus-kasus tragis di usia muda bukan sekadar “drama remaja.” Itu alarm bahwa kita sedang membiarkan anak-anak kehilangan hak mereka untuk menjadi anak-anak. Dunia orang dewasa terlalu cepat mereka masuki, terlalu mudah mereka tiru, dan terlalu berat mereka tanggung. Dan kita semua, mau tidak mau, ikut bertanggung jawab atas generasi yang dibesarkan oleh layar, tapi dibiarkan tersesat ketika emosinya meledak.
Editor: Aisyananda Salsabila