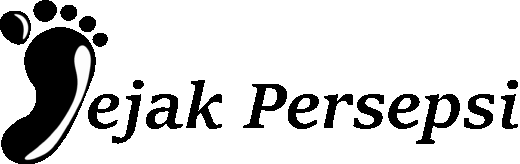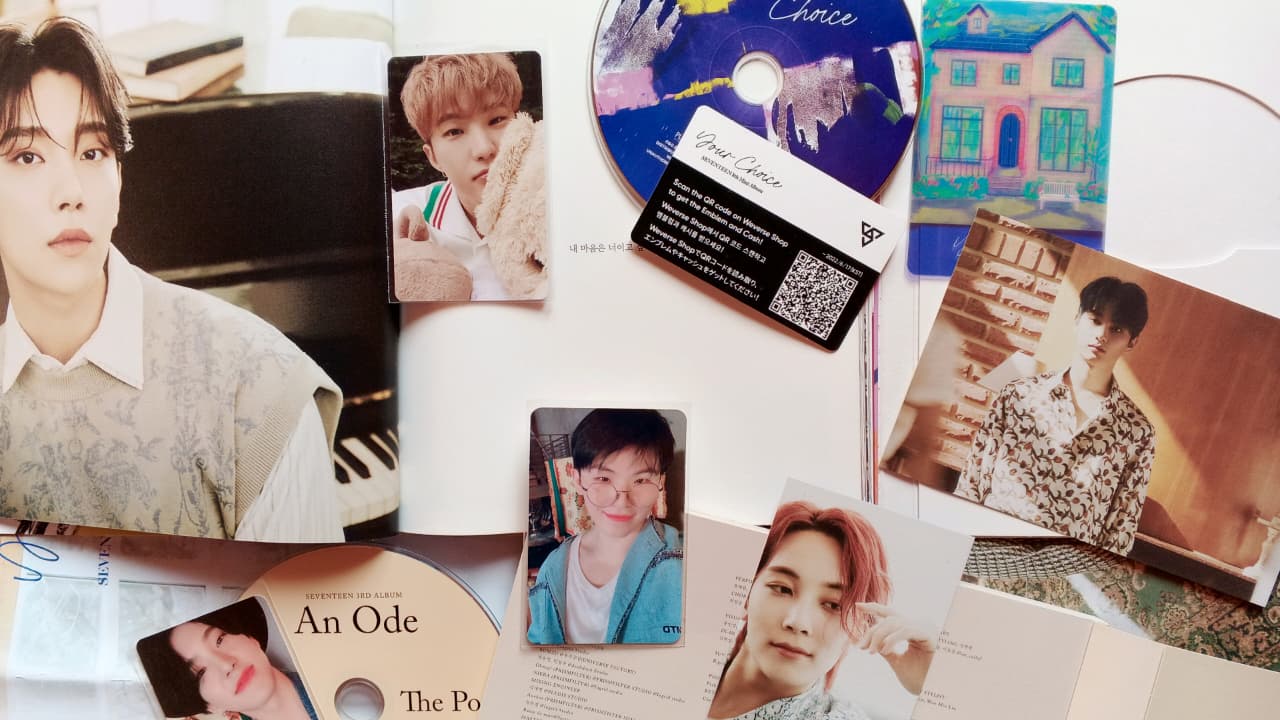Purwokerto— Istilah “ghosting” kini menjadi bagian dari kosa kata populer di kalangan generasi muda. Awalnya berasal dari bahasa Inggris ghost yang berarti hantu, istilah ini menggambarkan tindakan seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar dalam hubungan atau komunikasi. Namun, di era digital, ghosting telah meluas maknanya tidak hanya soal percintaan, tetapi juga pertemanan dan interaksi daring.
Dalam percakapan media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, kata “ghosting” sering digunakan secara santai, bahkan telah mengalami proses penyesuaian menjadi “nge-ghosting” atau “dighosting”. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa digital terus berkembang mengikuti pola komunikasi pengguna internet, terutama di kalangan generasi Z yang tumbuh di tengah arus teknologi.
Bagi sebagian orang, ghosting dianggap hal lumrah dalam komunikasi modern cepat, instan, dan sering kali tanpa keterikatan emosional. Namun, di sisi lain, tindakan ini dianggap mencerminkan menurunnya kualitas empati dalam hubungan sosial. Tidak jarang, para pengguna media sosial membagikan pengalaman “dighosting” dengan nuansa humor, sindiran, atau refleksi diri melalui konten kreatif.
Fenomena ghosting menjadi bukti bahwa media digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan bahasa baru yang merekam perilaku sosial masyarakat. Kata-kata seperti ghosting, unfollow, dan mute kini tidak sekadar istilah teknis, melainkan juga simbol cara manusia menavigasi hubungan di dunia maya.
Perubahan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi terus memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Melalui fenomena seperti ghosting, kita dapat melihat bagaimana generasi digital menyesuaikan bahasa untuk mengekspresikan pengalaman emosional dan sosial yang lahir dari interaksi daring mereka.
Editor: Naura Tsalatsa Zahra