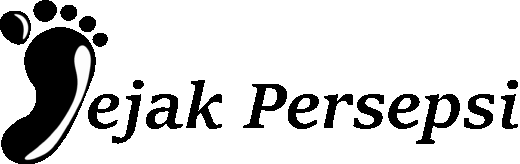(Sumber: photographyjoe)
Purwokerto – Tradisi Cowongan menjadi salah satu kekayaan budaya Banyumasan yang hingga kini terus dijaga keberadaannya. Titut Edi Purwanto, pemangku budaya sekaligus pelestari utama tradisi ini, mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap seni dan budaya sudah tumbuh sejak kecil. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan alam, sastra, dan kesenian. “Sejak kecil saya sudah suka melukis, baca puisi, nulis puisi, dan ikut kesenian seperti lengger. Jadi seni itu sudah ada dalam diri saya,” ujarnya.
Dari kecintaan itu, Titut merasa terpanggil untuk terlibat dalam pelestarian budaya Banyumasan, terutama Cowongan. Ia mulai secara serius menggeluti tradisi tersebut sejak tahun 2006 bersama istri dan teman-temannya. “Waktu itu saya merasa Cowongan harus diselamatkan, jangan sampai hilang. Dari situlah saya mulai belajar, mendalami, dan akhirnya mementaskan Cowongan,” kata Titut.

Cowongan sendiri merupakan karya seni petani yang lahir pada masa kemarau panjang atau mangsa ketiga dawa. Pada situasi tersebut, masyarakat menciptakan sebuah ritual untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar hujan segera turun. Tradisi ini menggunakan tempurung kelapa yang kemudian dicowang-caweng atau digambar menyerupai wajah perempuan. Tempurung itu dihias dengan areng kayu jati, diberi pakaian dari jerami kering sebagai simbol kekeringan, dan diyakini menggambarkan kehadiran Dewi yang mampu membawa hujan. Selain unsur visual, tradisi ini juga memuat kekuatan sastra lisan berupa mantra, tembang, dan syair yang menjadi bagian penting dari prosesi. “Syair-syairnya itu tentang cinta kasih, antara manusia dan alam, juga manusia dan Tuhan. Bukan musrik, bukan permainan setan,” tambahnya.
Pelaksanaan tradisi Cowongan pada masa lalu melibatkan lima orang dewasa yang telah menjalani puasa tiga hari tiga malam. Boneka cowongan ditempatkan di lokasi yang dianggap keramat, seperti pohon pisang raja atau area pemakaman, selama masa tirakat. Setelah itu, boneka dibawa pulang untuk menjalani ritual yang diiringi dupa dan tembang mantra. Jika boneka bergerak, masyarakat percaya bahwa Dewi telah hadir dan hujan akan turun dalam beberapa hari. Meski penuh unsur spiritual, tradisi ini tidak lepas dari nilai etika lokal yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan.
Sebagai pemangku budaya, Titut berperan besar dalam mengadaptasi ritual sakral tersebut menjadi seni pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ia bertindak sebagai dukun, sutradara, sekaligus pemandu jalannya pertunjukan. “Sekarang Cowongan sudah kami kemas jadi tontonan, tapi tetap dengan ruh aslinya. Syairnya masih kami pakai, musiknya juga khas Banyumasan,” tuturnya.
Tradisi Cowongan banyak ditemukan di Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, meskipun di beberapa daerah dikenal dengan nama berbeda. Dukungan pemerintah dan komunitas budaya juga semakin kuat, salah satunya melalui program seperti Jerami Feast dengan tema Cowongan dalam Bingkai Nusantara. Titut mengaku senang terlibat dalam pelestarian tradisi ini karena baginya Cowongan telah menjadi bagian dari jiwanya. “Saya senang, karena ini sudah jadi napas hidup saya,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa istri serta rekan-rekan komunitasnya menjadi sumber semangat terbesar dalam menjaga keberlanjutan Cowongan. Di akhir wawancara, Titut berharap seni dan budaya Banyumasan tetap dihargai dan diteruskan oleh generasi muda. “Harapan saya sederhana, cowongan jangan sampai hilang. Harus terus dikenal dan dilestarikan,” tutupnya.
Editor: Bunga Oktarina Rahadatul Aisy